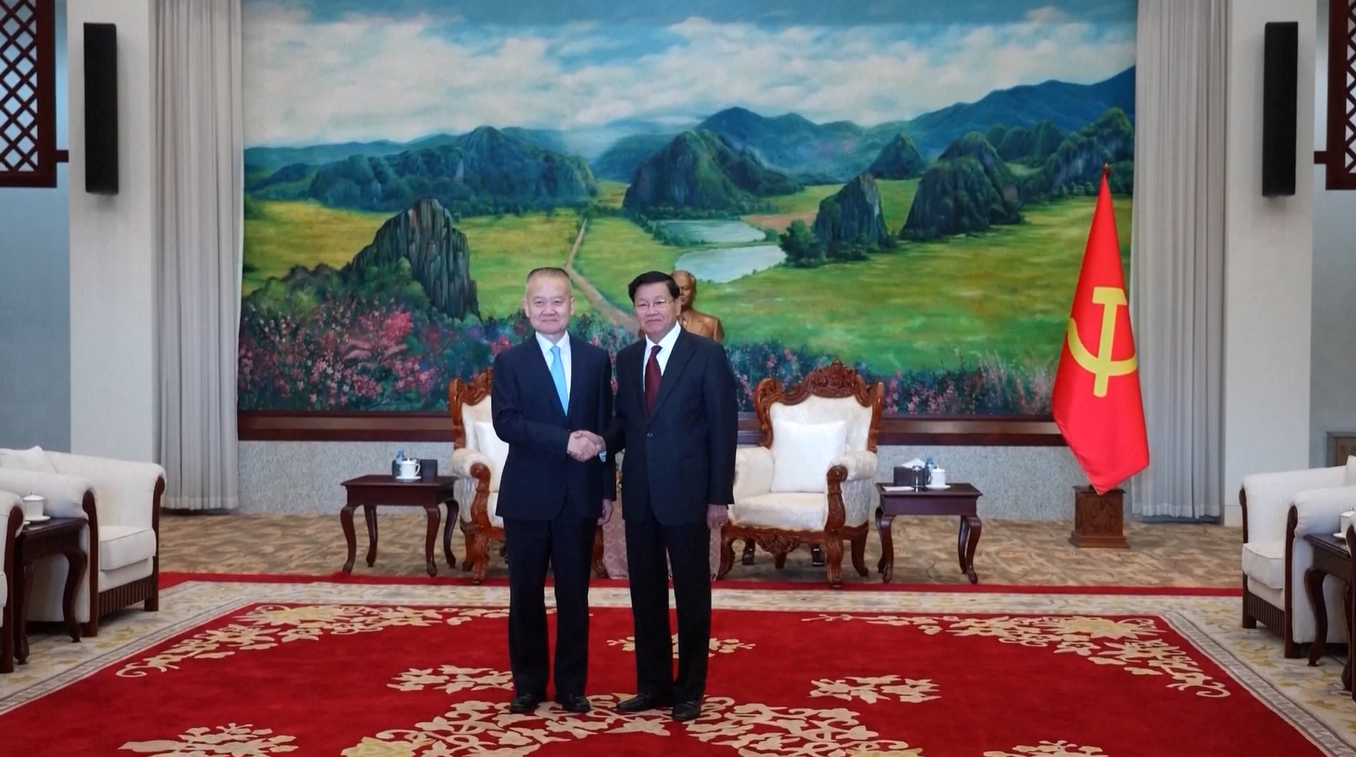Bharata Online - Pernyataan Amerika Serikat (AS), bahwa kepemilikan dan kendali atas Greenland mutlak diperlukan, adalah ekspansi hegemonik yang dikemas dalam narasi "legitimasi". Dengan menggunakan taktik tiga cabang — membingkai ulang narasi sejarah, menghubungkan masalah ini dengan masalah keamanan, dan mengikat kepentingan sumber daya, Washington berupaya menggambarkan ambisi teritorialnya sebagai "klaim yang sah".
Seruan AS untuk mendapatkan Greenland, telah mendorong Uni Eropa ke posisi yang tidak nyaman, memaksa blok tersebut untuk memilih, antara komitmennya yang diakui terhadap prinsip kedaulatan, dan ketergantungannya pada aliansi dengan AS. Ketegangan yang dihasilkan telah mengungkap keretakan dalam hubungan trans-atlantik.
Keinginan AS untuk menguasai Greenland, bukanlah keinginan tiba-tiba, melainkan konstruksi naratif sistematis, yang menyamarkan aneksasi sebagai pilihan yang selaras, dengan aturan dan kepentingan.
AS telah mengerahkan pesawat tempur F-35A berkemampuan ganda di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, dan mengaktifkan kembali unit tempur Arktik, mencoba melegitimasi kehadiran militernya, dan menumbuhkan persepsi palsu, bahwa "hanya AS yang dapat menjamin keamanan Greenland".
Dengan menegaskan bahwa AS hanya membela wilayahnya sendiri, Washington berupaya membingkai ulang aneksasi, sebagai pilihan yang tak terhindarkan, untuk memenuhi apa yang disebut sebagai tanggung jawab keamanannya.
NATO, sebagai pilar keamanan Eropa, tetap diam mengenai masalah Greenland. Pernyataan Sekretaris Jenderal Mark Rutte, bahwa ia tidak ingin melibatkan NATO, mengungkapkan bagaimana masalah kedaulatan dalam aliansi, telah sepenuhnya dibayangi oleh hegemoni AS.
Dalam laporan pertahanannya, untuk pertama kalinya Denmark menyebut AS sebagai potensi risiko keamanan. Kontradiksi ini melambangkan dilema Eropa: bagaimana mempertahankan prinsip kedaulatan, sambil menghindari konfrontasi dengan penjamin keamanannya. (China Daily)