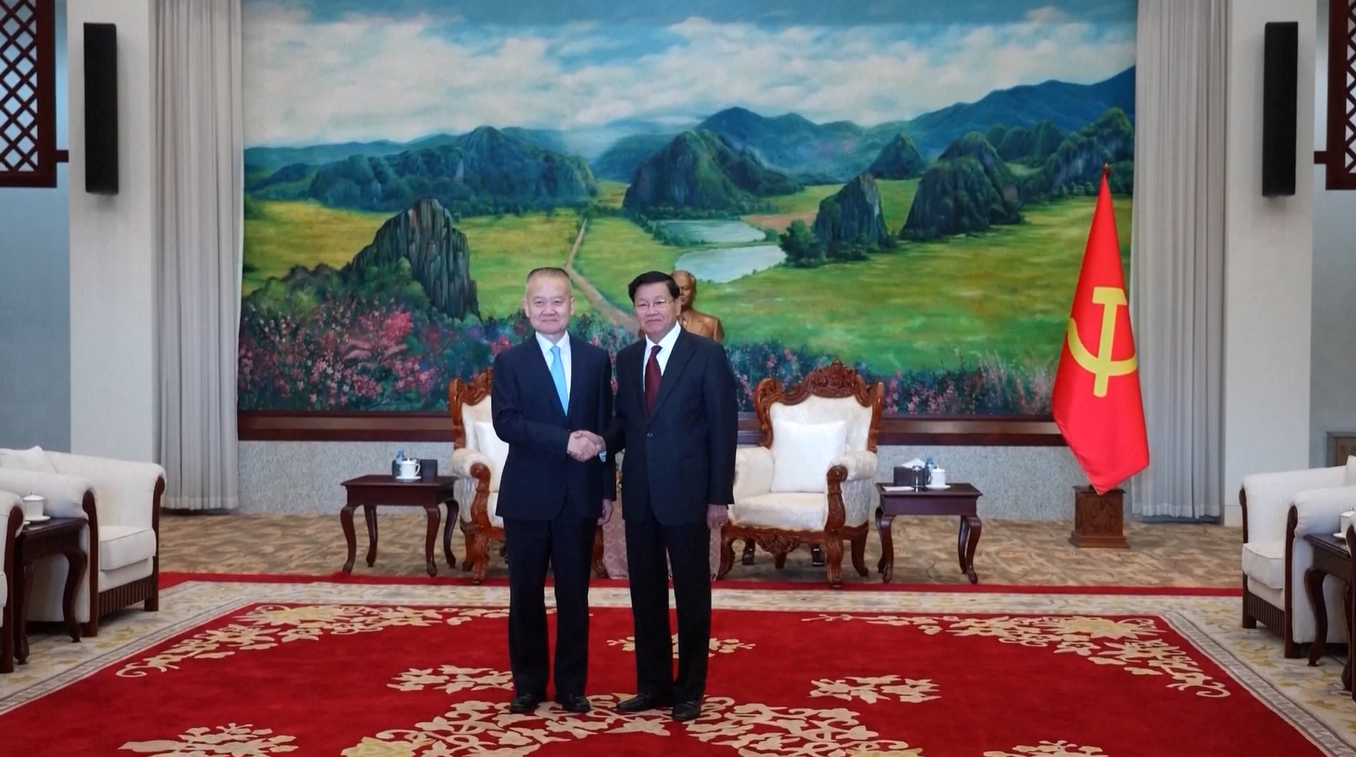Bharata Online - Narasi “perang terhadap narkoba” yang dipakai Amerika Serikat untuk menyerang Venezuela baru-baru ini sejatinya hanyalah tameng usang, sebuah alibi moral yang terdengar heroik di permukaan tapi rapuh dan tidak masuk akal ketika diuji dengan logika dan sejarah. Dengan dalih memberantas kokain, Amerika Serikat justru melancarkan serangan militer, menculik presiden negara berdaulat, dan menginjak-injak hukum internasional, seolah-olah kartel narkoba bisa runtuh hanya dengan menangkap satu kepala negara.
Ini bukan penegakan hukum, ini bukan keadilan global, melainkan panggung besar untuk melegitimasi agresi, menutup motif ekonomi dan geopolitik, serta menjual perang ke publik dunia dengan slogan yang sudah berkali-kali dipakai dan berkali-kali gagal namun tetap dipaksakan demi satu tujuan, yaitu menyerang Venezuela tanpa harus mengaku bahwa yang sebenarnya diburu bukan narkoba, melainkan kekuasaan, minyak, dan pengaruh.
Makanya kalau kita melihat fakta di lapangan, narasi “perang terhadap narkoba” seakan terdengar sangat familiar. Kenapa? Itu karena narasi semacam ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat memakai dalih tersebut. Panama tahun 1989, Kolombia, bahkan Afghanistan, semua pernah dibungkus dengan alasan moral yang terdengar mulia tersebut. Tapi hasil akhirnya hampir selalu sama, rezim diganti, sumber daya strategis diamankan, dan kepentingan geopolitik Amerika Serikat diperluas. Venezuela kali ini hanyalah episode terbaru dari serial panjang itu.
Sekarang mari kita bicara angka, karena angka biasanya tidak bisa bohong. Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel. Ini bukan angka kecil, ini hampir seperlima cadangan minyak global. Masalahnya, selama bertahun-tahun Venezuela tidak bisa memproduksi secara optimal karena sanksi, embargo, dan tekanan ekonomi dari Amerika Serikat sendiri. Tapi justru di situlah letak daya tariknya, karena bagi perusahaan minyak raksasa Amerika, Venezuela itu seperti ladang emas yang terkunci. Begitu gemboknya dibuka, nilainya luar biasa.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahkan tidak malu-malu mengatakannya. Dirinya sampai menyebutkan bahwa biaya operasi militer akan “dibayar dengan minyak Venezuela”. Ini bukan analisis spekulatif, tapi pengakuan langsung Trump. Jadi kalau masih ada yang bilang ini murni soal narkoba atau demokrasi, jujur saja, kita sedang diajak pura-pura bodoh.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif bagi Washington yaitu Tiongkok. Kita tau, selama lebih dari satu dekade terakhir, ketika Amerika Serikat menutup pintu lewat sanksi, Tiongkok justru masuk ke Venezuela lewat pintu kerja sama melalui pinjaman berbasis minyak, investasi infrastruktur, perdagangan energi, dan hubungan diplomatik yang relatif stabil.
Makanya, wajar saja jika pada tahun 2025 kemarin terdapat sekitar 80 persen ekspor minyak Venezuela mengalir ke Tiongkok, sebagian besar sebagai pembayaran utang. Dengan kata lain, Venezuela bukan cuma mitra biasa bagi Beijing, tapi bagian penting dari strategi energi dan ekonomi globalnya. Disinilah kita bisa melihat invasi ini dari kacamata yang lebih jujur, bahwa ternyata Amerika Serikat bukan cuma menyerang Venezuela, tapi juga serangan tidak langsung ke Tiongkok.
Amerika Serikat tahu betul bahwa pengaruh Tiongkok di Amerika Latin sedang naik daun. Data perdagangan bicara sangat jelas, bayangkan saja pada tahun 2000 kontribusi Tiongkok ke perdagangan Amerika Latin bahkan tidak sampai 2 persen. Tapi coba lihat pada tahun 2024? Angkanya tembus 518 miliar dolar Amerika atau sekitar 8.701 triliun rupiah.
Proyeksi ke depan bahkan bisa melebihi 700 miliar dolar Amerika atau sekitar 11.758 triliun rupiah pada tahun 2035. Makanya Tiongkok sudah jadi mitra dagang utama Amerika Selatan, dan itu terjadi bukan lewat invasi tapi lewat bisnis, infrastruktur, dan pembiayaan pembangunan. Bagi Amerika Serikat, ini jelas adalah ancaman strategis.
Apalagi sejak Trump menghidupkan kembali versi ekstrem Doktrin Monroe, yang sekarang dikenal sebagai “Trump Corollary”. Apa itu? Intinya sederhana bahwa belahan Barat atau wilayah Amerika bagian Utara dan Selatan termasuk Karibia harus di bawah kendali Amerika Serikat, bukan cuma secara politik dan militer, tapi juga ekonomi dan sumber daya.
Jadi ketika Venezuela terlalu dekat dengan Tiongkok, bagi Washington itu sudah dianggap pelanggaran “wilayah kekuasaan”. Artinya, dalam kebijakan Trump Corollary tersebut pengaruh asing dalam hal ini Tiongkok harus dibendung dan dikeluarkan dari wilayah tersebut bagaimanapun caranya agar tidak menjadi gangguan bagi dominasi mereka.
Sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan kacamata yang lebih santai. Amerika datang ke Venezuela dengan kapal perang, pasukan, bom, dan penangkapan paksa presiden. Tiongkok datang dengan diplomat, kontrak dagang, pinjaman, dan proyek infrastruktur. Yang satu datang dengan ancaman, yang satu datang dengan penawaran. Pertanyaannya sederhana, negara berkembang mana yang tidak lebih nyaman dengan pendekatan Tiongkok?
Di sinilah posisi Tiongkok menjadi menarik secara moral dan politik. Beijing konsisten mengatakan satu hal bahwa kedaulatan negara harus dihormati, masalah internal harus diselesaikan lewat dialog, bukan senjata. Ini bukan sekadar omong kosong, karena kita bisa lihat sikap Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka menentang invasi Amerika Serikat dan menyerukan pembebasan Maduro.
Bahkan ketika kepentingan ekonominya terancam, utang miliaran dolar, pasokan minyak terganggu, nyatanya Tiongkok tetap tidak mengirim pasukan atau mengancam serangan balik. Bandingkan dengan Amerika Serikat, yang mengklaim diri sebagai pembela tatanan berbasis aturan, tapi justru melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara terang-terangan.
Ini ironi yang makin sulit ditutupi, karena dunia internasional melihatnya, negara-negara Selatan Global atau negara-negara berkembang melihatnya, dan pelan-pelan kepercayaan terhadap moral leadership Amerika Serikat mulai terkikis. Itulah mengapa, pengaruh Tiongkok semakin tinggi dan Amerika Serikat justru menurun.
Sekarang mari kita lihat soal narkoba. Benar bahwa Venezuela memang jalur transit penting, tapi jujur saja apakah kartel narkoba lahir karena Maduro? Apakah perdagangan narkoba akan hilang kalau Maduro ditangkap? Sejarah menunjukkan jawabannya tidak. Selama permintaan narkoba di Amerika Serikat tinggi, selama sistem ekonomi gelap itu menguntungkan, jalurnya akan selalu ada. Itu artinya, mengganti rezim hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Di sisi lain, ada agenda domestik Amerika Serikat yang jarang dibahas terang-terangan yaitu terkait imigran Venezuela. Sekitar 700 ribu warga Venezuela ada di Amerika Serikat. Dengan menguasai negaranya, Amerika Serikat punya legitimasi politik untuk memulangkan mereka secara paksa. Jadi, ini cocok dengan janji kampanye Trump, makanya invasi ini juga punya nilai jual politik dalam negeri, bukan cuma geopolitik luar negeri.
Lalu bagaimana dampaknya ke dunia? Menariknya, harga minyak global relatif stabil. Ini menunjukkan satu hal penting bahwa secara jangka pendek, Venezuela tidak sepenting itu bagi pasar minyak global. Tapi justru disinilah jebakannya, karena Amerika Serikat mungkin bisa menguasai Venezuela, tapi butuh waktu 5 sampai 10 tahun dan investasi miliaran dolar untuk benar-benar menghidupkan kembali industri minyaknya. Selama itulah, ketidakstabilan politik akan terus menghantui.
Bagi Tiongkok, situasinya jelas tidak ideal, tapi setidaknya jauh dari bencana. Beijing punya diversifikasi energi, punya kapasitas ekonomi besar, dan punya jalur hukum internasional. Bahkan jika Venezuela kelak dipimpin rezim baru yang tidak ramah, Tiongkok masih bisa bernegosiasi langsung, tanpa harus tunduk pada tekanan militer seperti yang dilakukan Amerika Serikat.
Dan di titik inilah kita bisa menarik kesimpulan besar bahwa apa yang kita lihat di Venezuela bukanlah kebangkitan kekuatan Amerika, melainkan tanda kegelisahan. Ini adalah reaksi hegemon lama yang merasa posisinya terancam. Sebaliknya, Tiongkok justru terlihat semakin percaya diri, tenang, dan konsisten dengan pendekatannya.
Untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pelajaran dari Venezuela ini sangat jelas. Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar. Dalam tatanan ini, kekuatan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling sering menembakkan rudal, tapi siapa yang paling mampu menawarkan kerja sama yang stabil, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan.
Sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah invasi Amerika Serikat ke Venezuela akan membuat dunia lebih aman, lebih stabil, dan lebih adil? Atau sebaliknya, memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis kekuatan militer sudah usang? Di tengah semua kekacauan ini, satu hal justru semakin terang bahwa model Tiongkok yang tanpa invasi, tanpa ganti rezim, tanpa mengklaim diri sebagai polisi dunia nampaknya semakin relevan di mata banyak negara. Dan mungkin, tanpa disadari, langkah Amerika di Venezuela justru menjadi iklan gratis bagi visi dunia multipolar yang selama ini diperjuangkan Tiongkok.