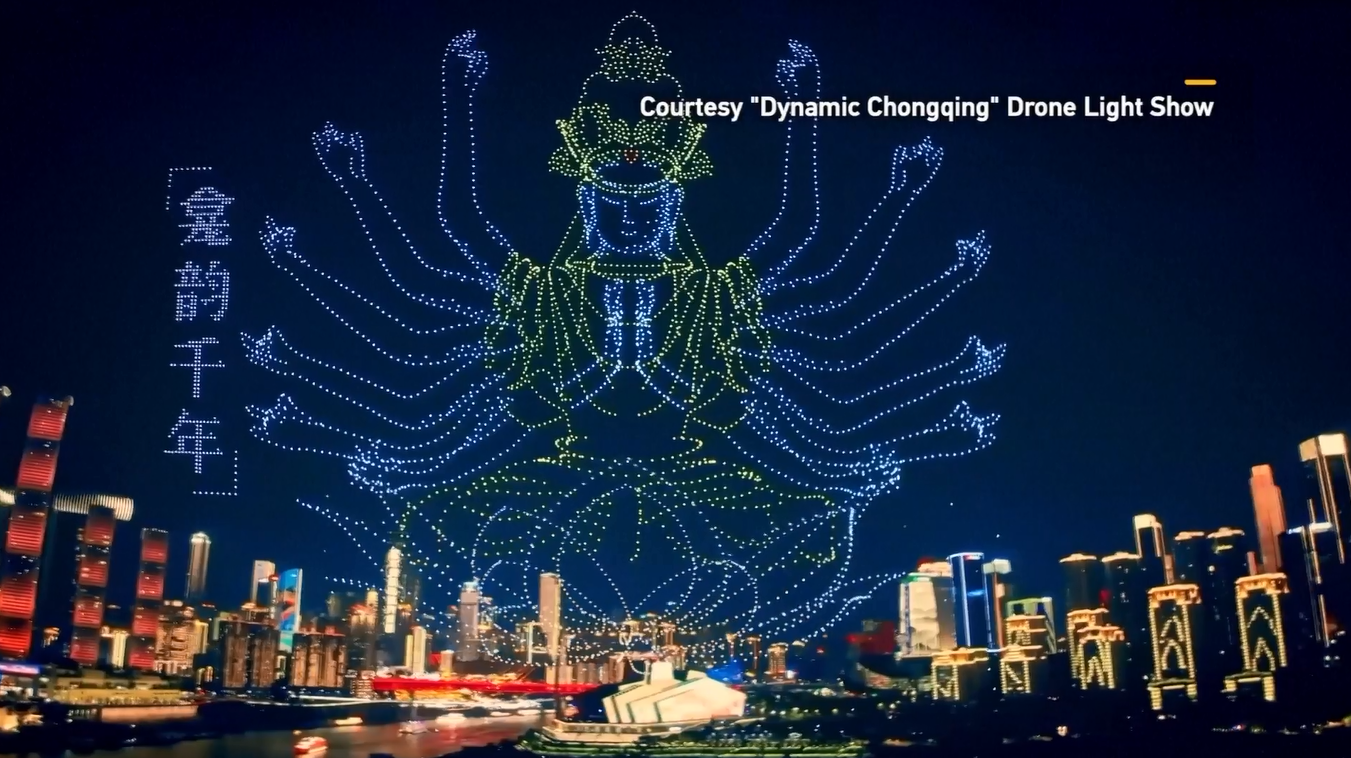Bharata Online - Rilisnya gim Where Winds Meet pada 15 November 2025 bukan hanya peristiwa hiburan digital, tetapi representasi paling mutakhir dari transformasi struktural industri gim Tiongkok dan lonjakan kekuatan lunak (soft power) yang mulai mengguncang tatanan global.
Gim ini, yang dibangun Everstone Studio dan dipublikasikan Netease, hadir dengan kualitas visual dan narasi Wuxia yang mengingatkan dunia bahwa Tiongkok tidak lagi sekadar “pabrik tiruan,” melainkan pusat inovasi budaya yang mampu menyaingi bahkan mengungguli hegemoni Amerika Serikat (AS) dan Barat hingga Jepang yang selama ini memonopoli lanskap gim internasional.
Fenomena ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar, di mana Tiongkok mulai memposisikan permainan digital sebagai instrumen soft power yang strategis, dengan efek ekonomi, budaya, dan diplomatik yang sulit diabaikan.
Where Winds Meet menegaskan bahwa kualitas bukan lagi milik eksklusif studio-studio di AS dan Barat maupun Jepang. Dunia terbuka dengan sistem ekologi dinamis, pertarungan fleksibel, gerakan khas pendekar Wuxia, hingga mode ko-op berskala besar menunjukkan lompatan teknologi yang lahir dari riset jangka panjang, dukungan pemerintah, dan ekosistem talenta domestik yang kini jauh lebih matang.
Ini kontras dengan industri gim Barat yang dalam beberapa tahun terakhir terus diwarnai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, penurunan inovasi, microtransaction agresif, dan ketergantungan pada franchise lama. Dengan kata lain, ketika Barat sedang stagnan, Tiongkok bergerak agresif. Begitu pula ketika perusahaan Amerika “memerah” kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) lawas, studio Tiongkok justru menciptakan dunia baru.
Sukses masif Black Myth: Wukong pada tahun 2024 adalah titik balik historis yang membuka mata dunia. Dalam tiga hari gim itu terjual 10 juta kopi, sebuah pencapaian yang secara objektif hanya bisa diraih oleh segelintir developer global. Yang membuatnya lebih signifikan bukan semata angka penjualan, tetapi bagaimana gim tersebut digunakan oleh pemerintah Tiongkok sebagai “visa budaya” untuk memperkenalkan warisan filosofis, estetika, dan narasi klasik Tiongkok ke audiens global.
Di sinilah perbedaan strategis muncul yang mana AS masih menggunakan film Hollywood sebagai tumpuan soft power, sementara Tiongkok memahami bahwa generasi global berusia 12–35 tahun kini lebih banyak mengonsumsi budaya melalui gim, e-sports, dan platform digital interaktif. Data memperkuat perubahan ini yang mana pada tahun 2024–2025, pasar gim Tiongkok mencapai pendapatan dalam negeri lebih dari 325 miliar yuan (sekitar 764 triliun rupiah), dan di semester awal tahun 2025 naik menjadi 168 miliar yuan (sekitar 395 triliun rupiah).
Dengan hampir 700 juta pemain domestik yang tiga kali lipat lebih banyak dari populasi gamer Amerika, Tiongkok menguasai pasar yang bisa digunakan untuk melakukan eksperimen, mengembangkan inovasi, dan membangun fondasi studio yang stabil.
Ditambah, pendapatan luar negeri gim buatan Tiongkok kini mencapai 18,5 miliar dolar AS (sekitar 309 triliun rupiah), dengan Amerika sebagai pasar utamanya, diikuti Jepang dan Korea Selatan. Artinya, negara-negara yang selama ini diposisikan media Barat sebagai “pemimpin industri gim” kini justru menjadi konsumen dominan dari produk Tiongkok. Secara struktural, hubungan ini menciptakan dependensi budaya baru yang jarang dibahas oleh analis Barat.
Lonjakan minat wisata ke Shanxi dan Lianyungang setelah muncul di Black Myth: Wukong memperlihatkan bagaimana gim menjadi instrumen ekonomi nyata. Shanxi mengalami lonjakan turis hingga 50% hanya dalam satu bulan. Temuan ini sangat penting dalam kacamata teori soft power Joseph Nye bahwa pengaruh budaya yang efektif adalah pengaruh yang menghasilkan tindakan, bukan sekadar reputasi.
Jika anime Jepang menggerakkan turisme ke Akihabara atau film Hollywood menjual “American Dream”, maka gim Tiongkok kini mulai menggerakkan mobilitas sosial dan ekonomi lintas wilayah secara konkret. Jepang membutuhkan puluhan tahun untuk mencapai efek budaya semacam ini, sementara Tiongkok melakukannya dalam hitungan dua–tiga tahun.
Fenomena ini tidak terlepas dari strategi kebijakan yang lebih besar. Pemerintah Tiongkok menjadikan video gim sebagai bagian dari kebijakan budaya nasional. Tencent dan NetEase terus menerima dorongan untuk memperluas ekspor konten digital, sekaligus integrasi dengan e-sports yang menjadi cabang resmi Asian Games 2026 di Aichi–Nagoya. Guangdong merilis 87 kebijakan untuk memperkuat industri hiburan, sementara berbagai provinsi berlomba memanfaatkan momentum gim untuk memperkuat identitas lokal.
Ini berbeda dengan AS yang lebih mengandalkan pasar bebas sebagai motor inovasi, sebuah pendekatan yang kini tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan dan skala organisasi industri Tiongkok. Jepang yang pernah berada di puncak “kejayaan gim Asia”, justru stagnan akibat populasi yang menua, pasar domestik yang mengecil, dan ketergantungan pada IP lama seperti Final Fantasy, Pokemon, atau Tekken.
Di sisi lain, daftar sepuluh gim Tiongkok 2026 dari Parasite Mutant hingga Tides of Annihilation menggambarkan betapa agresifnya penciptaan genre baru yang tidak terjebak pada satu pola. Seperti Ananta yang menghapus sistem gacha karakter, Neverness to Everness (NTE) memperkenalkan open-world urban ala GTA, Tides of Annihilation memadukan mitologi Inggris dengan estetika timur, Phantom Blade Zero menawarkan animasi pertarungan yang membuat banyak gim AAA Barat terlihat ketinggalan satu dekade.
Jika Jepang pernah mendominasi era PS2 dan Amerika mendominasi era PS3–PS4, maka era pasca-2024 mulai memperlihatkan dominasi baru yang datang dari Tiongkok.
Dari perspektif hubungan internasional, transformasi ini bisa dibaca melalui pendekatan complex interdependence atau saling ketergantungan kompleks yang mana budaya digital menciptakan jejaring pengaruh yang lebih halus daripada kekuatan militer atau ekonomi. Menguasai gim berarti menguasai imajinasi generasi muda global.
Ketika jutaan gamer Barat menghabiskan ratusan jam dalam dunia-dunia digital buatan Tiongkok, mereka secara tidak sadar mulai menyerap nilai, estetika, dan narasi yang melekat di dalamnya. Ini adalah bentuk soft power yang bahkan tidak bisa dicapai oleh kebijakan luar negeri AS yang selama ini bertumpu pada strategi militer dan ekonomi yang keras.
Walaupun demikian, objektivitas tetap diperlukan. Tiongkok memang masih menghadapi tantangan seperti regulasi ketat, sensor konten, dan pembatasan waktu bermain anak. Namun, kendala-kendala ini tidak menghentikan pertumbuhan industri dan justru menjadi sistem filter yang menjamin gim berkualitas tinggi dan bebas dari eksploitasi berlebihan.
Ini berbeda dengan pasar Barat yang sering dikritik karena microtransaction agresif, lootbox, dan orientasi profit jangka pendek. Tiongkok menunjukkan bahwa regulasi yang tepat dapat menciptakan ekosistem yang sehat sekaligus kompetitif.
Pada akhirnya, Where Winds Meet, Black Myth: Wukong, dan deretan game 2026 lainnya bukan sekadar produk hiburan. Mereka adalah barisan depan dari revolusi soft power Tiongkok yang mengusung keyakinan bahwa budaya, teknologi, dan industri kreatif harus menjadi alat diplomasi global yang efektif.
Ketika gim Tiongkok disambut antusias di AS, Jepang, dan Korea Selatan bahkan menjadi sumber pendapatan utama di negara-negara tersebut, kita sedang menyaksikan perubahan arah sejarah. Untuk pertama kalinya dalam dekade-dekade terakhir, hegemoni budaya AS-Barat tidak lagi tak tergoyahkan.
Dan jika tren ini terus berlanjut, Tiongkok mungkin tidak lagi sekadar menjadi raksasa ekonomi, tetapi juga pusat gravitasi baru dalam peta budaya digital dunia. Oleh karena itu, gim bukan lagi permainan tapi diplomasi dan politik. Makanya bagi Tiongkok, gim adalah cara paling halus namun paling efektif untuk memenangkan hati dunia tanpa menembakkan satu peluru pun.