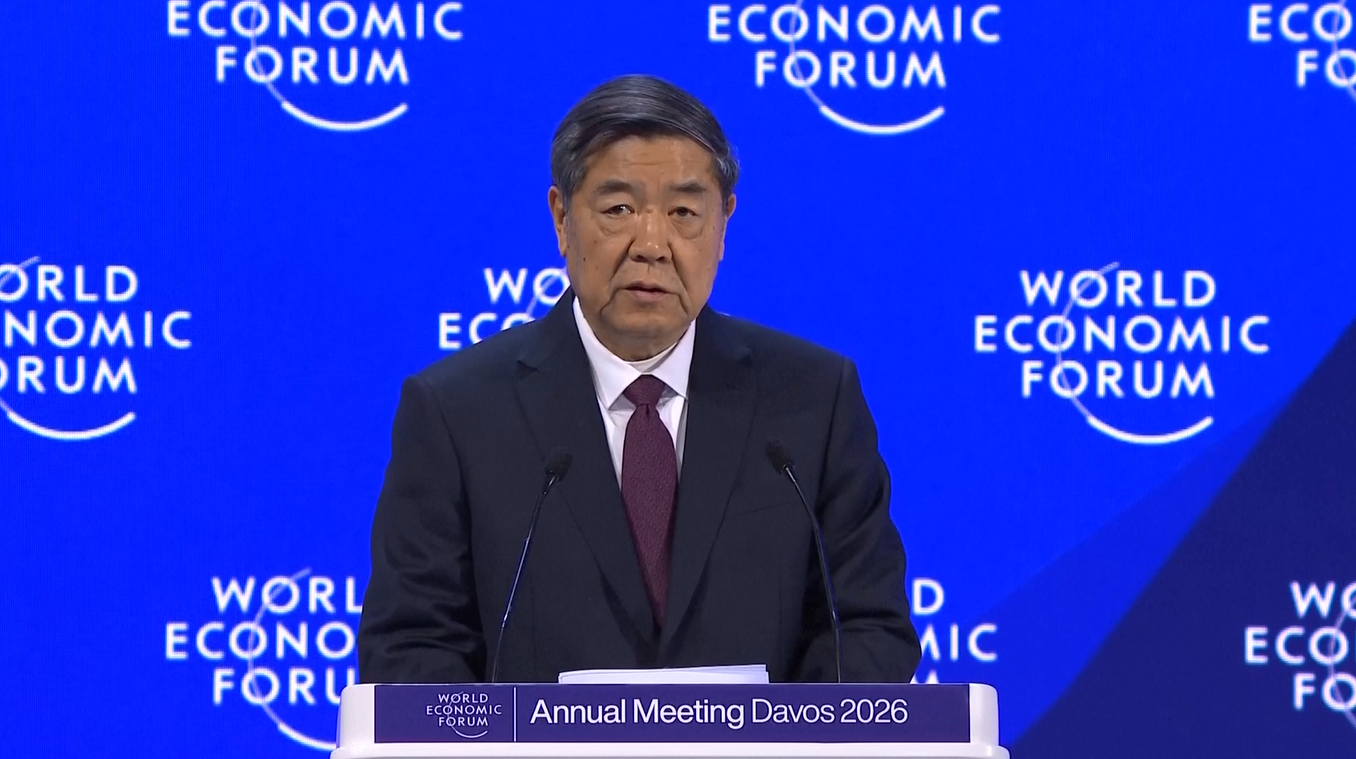Bharata Online - Ketegangan terbaru antara Tiongkok dan Jepang yang dipicu oleh pernyataan provokatif Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan dan rencana penempatan rudal Jepang di Pulau Yonaguni menjadi salah satu ketegangan geopolitik paling signifikan di Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Di satu sisi, langkah Jepang jelas dimaksudkan untuk menunjukkan posisi keamanan yang lebih agresif. Namun di sisi lain, krisis ini justru memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih penting bahwa kekuatan struktural Tiongkok yang kini telah mencapai titik, membuat reaksi Beijing dapat mengguncang fondasi ekonomi Jepang hanya dalam hitungan hari.
Fenomena ini bukan lagi soal perselisihan diplomatik biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana arsitektur geopolitik baru sedang terbentuk dengan Tiongkok tampil sebagai aktor dominan, sementara Jepang semakin terpukul akibat kesalahan kalkulasi strategisnya.
Krisis bermula ketika Takaichi menyatakan bahwa serangan hipotesis Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Jepang. Ini bukan sekadar komentar biasa, karena dari perspektif politik internasional pernyataan tersebut menabrak garis merah diplomatik terkait “Prinsip Satu Tiongkok”, yang telah menjadi dasar hubungan Tiongkok–Jepang sejak Komunike Bersama 1972.
Pernyataan itu langsung dibaca Beijing sebagai bentuk intervensi bersenjata serta pelanggaran berat terhadap norma diplomasi internasional. Tidak mengherankan jika Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyebut langkah Jepang itu sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan upaya menciptakan ketegangan regional.
Secara teoritik, dinamika ini dapat dianalisis menggunakan perspektif realisme. Dalam paradigma ini, negara bertindak berdasarkan kepentingan keamanan dan perimbangan kekuatan. Tiongkok, sebagai kekuatan besar yang terus naik, tidak akan membiarkan negara mana pun terlebih Jepang, negara yang secara historis memiliki rekam jejak agresi di Asia mengusik urusan dalam negerinya.
Taiwan, dalam logika realisme, bukan sekadar wilayah, tetapi simbol kedaulatan dan fondasi stabilitas internal Tiongkok. Karena itu, setiap pernyataan yang membuka kemungkinan intervensi asing dianggap ancaman eksistensial yang menuntut respons tegas.
Namun krisis ini bukan hanya persoalan militer. Justru dampak paling cepat terasa muncul dari sektor ekonomi Jepang. Teori interdependensi kompleks menjelaskan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, konflik politik akan menghasilkan efek samping besar pada perdagangan, pasar, mobilitas manusia, dan sektor industri.
Artinya, ketika Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan dan imbauan bagi warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, efeknya seperti gelombang tsunami ekonomi.
Kita bisa lihat dalam hitungan hari, sekitar 500.000 tiket penerbangan dibatalkan, tingkat pembatalan penerbangan mencapai 21,6%, dan maskapai-maskapai utama Tiongkok seperti Air China, China Eastern, hingga Xiamen Airlines mengumumkan kebijakan pengembalian dana penuh.
Data dari Umetrip memperlihatkan bahwa pembatalan tiket dari Tiongkok ke Jepang meningkat 12 kali lipat dibanding minggu sebelumnya. Sektor pariwisata Jepang, yang menyumbang sekitar 7% Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, langsung terpukul keras.
Takahide Kiuchi, seorang peneliti di Nomura Research Institute, telah memperingatkan bahwa sengketa diplomatik antara Jepang dan Tiongkok dapat mengurangi PDB Jepang lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 183 triliun rupiah selama tahun depan, dan itu akan menjadi penurunan PDB hampir 0,3 persen.
Hokkaido, destinasi favorit wisatawan Tiongkok melaporkan lonjakan pembatalan hotel dan tur. Sapporo Stream Hotel, yang biasanya menampung sekitar 3.000 wisatawan Tiongkok setiap bulan, telah mengalami sekitar 70 pembatalan pemesanan. Perusahaan East Japan International Travel Service mengatakan 70 persen dari rombongan tur Tiongkoknya telah dibatalkan.
Selain itu, pasar keuangan di Jepang juga merasakan tekanan. Meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kesehatan fiskal negara tersebut telah menyebabkan kemerosotan di pasar saham, dengan Nikkei turun 2,2 persen pada 21 November lalu dan turun 3,3 persen selama seminggu.
Saham ritel, kosmetik, perhotelan, dan sektor pariwisata juga anjlok. Shiseido turun 9 persen, Isetan Mitsukoshi merosot lebih dari 11 persen, operator restoran seperti Sushiro jatuh hampir 14 persen, dan berbagai perusahaan lain mengalami tekanan signifikan.
Turis Tiongkok sendiri menyumbang sekitar 27 persen belanja wisatawan asing di Jepang pada kuartal lalu dari total konsumsi wisatawan asing senilai 2,1 triliun yen atau sekitar 223 triliun rupiah, sehingga langkah Beijing jelas memberikan pukulan ekonomi yang sangat nyata.
Pemerintah Tiongkok juga menangguhkan penayangan setidaknya dua film Jepang menyusul memburuknya hubungan diplomatik antara Beijing dan Tokyo. Dua film yang terdampak adalah Crayon Shin-chan The Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers dan adaptasi manga Cells at Work! yang sebelumnya dijadwalkan tayang dalam beberapa minggu ke depan.
Ketegangan ini juga berimbas pada industri hiburan yang lebih luas. Film Demon Slayer: Infinity Castle, yang semula mencatat antusiasme tinggi dari penonton Tiongkok, dilaporkan mengalami penurunan penjualan tiket setelah komentar Takaichi.
Di pasar keuangan, kabar penundaan film berdampak langsung pada saham perusahaan hiburan Jepang. Data dari Investing.com menunjukkan bahwa saham perusahaan-perusahaan yang terkait dengan distribusi anime dan film Jepang mengalami penurunan signifikan pada hari pengumuman.
Toho Co., perusahaan besar yang menangani berbagai judul film Jepang di pasar internasional, dilaporkan mengalami penurunan harga saham akibat kekhawatiran akan blokade budaya yang lebih besar dari Tiongkok.
Itulah mengapa, pasar menilai bahwa setiap hambatan terhadap rilis konten Jepang di Tiongkok bisa berpengaruh besar, mengingat Tiongkok adalah salah satu pasar konsumen terbesar untuk produk animasi dan sinema Jepang.
Semua fakta ini mengilustrasikan ketergantungan struktural Jepang terhadap wisatawan dan konsumen Tiongkok. Inilah yang disebut para ekonom sebagai “kerentanan asimetris”, ketergantungan dua arah tetapi satu pihak jauh lebih rentan. Makanya dalam hal ini, Tiongkok mampu memberi dampak besar hanya dengan kebijakan administratif sederhana, sedangkan Jepang praktis tidak memiliki alat serupa untuk memberi tekanan balik.
Konsekuensi ekonomi ini mencerminkan lensa liberal institusionalisme. Dalam teori ini, kerja sama internasional dibangun atas dasar stabilitas, kepercayaan, dan norma bersama. Ketika Jepang merusak stabilitas tersebut melalui kebijakan keamanan yang provokatif, hubungan ekonomi yang selama ini menjadi penopang kesejahteraan kedua negara ikut goyah.
Nomura Research Institute memperkirakan bahwa Jepang berpotensi mengalami kerugian sekitar 2,2 triliun yen atau sekitar Rp237 triliun, jika penurunan wisatawan Tiongkok berlangsung lama. Ini setara dengan penurunan PDB sebesar 0,36%, angka yang sangat besar untuk ekonomi maju.
Namun dimensi paling menarik dari krisis ini sesungguhnya terlihat pada sektor otomotif Jepang. Dalam Pameran Otomotif Guangzhou ke-23, hanya beberapa pekan setelah pernyataan Takaichi, merek Jepang seperti Toyota, Honda, dan Nissan tampak tersingkir dari pusat perhatian.
Pangsa pasar mereka di Tiongkok turun menjadi di bawah 11,2%, angka terendah dalam sejarah modern industri otomotif Jepang. Keterpurukan ini bukan semata-mata akibat faktor geopolitik, tetapi juga karena Tiongkok telah secara dominan memenangkan kompetisi teknologi, khususnya di sektor kendaraan listrik.
Dari perspektif realisme ekonomi, negara yang unggul dalam teknologi strategis akan menguasai pasar global. Tiongkok telah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dengan produksi baterai, teknologi otonom, digitalisasi kendaraan, serta dukungan kebijakan industri yang kuat.
Sementara itu, Jepang terlalu lama bertahan pada teknologi hybrid dan mesin pembakaran internal. Ketika konsumen Tiongkok semakin melek teknologi dan memilih mobil listrik canggih, merek Jepang semakin kehilangan relevansi.
Pernyataan Takaichi menjadi katalis yang mempercepat keruntuhan reputasi industri otomotif Jepang. Konsumen Tiongkok, dalam konteks konstruktivisme, memaknai pembelian mobil bukan hanya sebagai transaksi ekonomi tetapi juga ekspresi identitas nasional.
Ketika Jepang dinilai menantang kedaulatan Tiongkok, publik Tiongkok memberikan respons ekonomi yang kuat. Inilah yang disebut “konsumerisme nasionalis”, fenomena ketika konsumen menjadikan identitas politik sebagai dasar pilihan pasar.
Efek berantai pun terjadi. Pabrik-pabrik Jepang di Tiongkok mulai mengurangi produksi, menutup lini tertentu, dan menunda investasi baru. Toyota, Honda, dan Nissan menghadapi tekanan struktural yang berpotensi melemahkan daya saing global mereka dalam jangka panjang.
Sementara itu, perusahaan otomotif Tiongkok seperti BYD, Li Auto, NIO, dan HiPhi justru semakin memperluas pasar dan reputasi teknologi mereka.
Krisis ini memperlihatkan pergeseran yang lebih dalam dalam hubungan Tiongkok–Jepang. Jepang kini berada dalam posisi dilematis, di satu sisi ingin menegaskan peran geopolitiknya bersama Amerika Serikat, namun di sisi lain ekonomi domestiknya sangat bergantung pada Tiongkok. Inilah kontradiksi strategis yang oleh para akademisi internasional disebut sebagai “perangkap strategis”, yang membuat Jepang terjebak antara komitmen keamanan terhadap Amerika Serikat dan kebutuhan ekonomi terhadap Tiongkok.
Sementara Jepang mengalami tekanan dari berbagai sektor, Tiongkok justru memperlihatkan konsistensi kebijakan yang stabil. Kritik Beijing terhadap Jepang bukan hanya reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi diplomasi tegas yang mempertahankan posisi hukum internasional mengenai Taiwan sebagai urusan dalam negeri Tiongkok.
Dalam kerangka realisme defensif, tindakan Tiongkok dipandang sebagai langkah mempertahankan stabilitas regional dari upaya provokatif yang dapat memicu konflik tidak perlu.
Namun bukan hanya Tiongkok yang mengecam Takaichi. Di Jepang sendiri, para mantan perdana menteri seperti Yukio Hatoyama dan Yoshihiko Noda menilai pernyataan Takaichi gegabah dan berbahaya. Partai oposisi, akademisi, hingga beberapa tokoh politik sayap kiri menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menyeret Jepang ke dalam konflik besar.
Bahkan Ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, Mizuho Fukushima, menyatakan bahwa menggunakan masalah Taiwan sebagai legitimasi peningkatan kekuatan militer adalah langkah yang tidak bertanggung jawab. Reaksi-reaksi ini menunjukkan bahwa di Jepang sendiri terdapat kesadaran kuat bahwa stabilitas hubungan Tiongkok–Jepang adalah kunci bagi masa depan ekonomi dan keamanan kawasan.
Namun pemerintahan Takaichi tampaknya memilih jalan yang berisiko tinggi dengan mendorong agenda militerisasi, termasuk mempertimbangkan revisi Tiga Prinsip Non-Nuklir, yang memicu kekhawatiran baru di Asia Timur.
Krisis ini membuktikan bahwa di dunia multipolar saat ini, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh militer, tetapi oleh kapabilitas ekonomi, ketahanan sosial, pengaruh teknologi, dan kemampuan memobilisasi opini publik global. Di semua aspek tersebut, Tiongkok kini berada pada posisi yang lebih kuat dibanding Jepang.
Pada akhirnya, ketegangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri yang gegabah dapat menghancurkan miliaran dolar ekonomi dalam hitungan hari. Jepang sedang merasakan dampaknya secara langsung.
Sementara itu, Tiongkok dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar, industri teknologi yang lebih maju, serta posisi geopolitik yang semakin kokoh menunjukkan bahwa stabilitas, rasionalitas diplomatik, dan kekuatan struktural adalah fondasi utama dalam menentukan arah masa depan Asia Timur.
Krisis ini menjadi pelajaran penting bagi Jepang bahwa tanpa pendekatan diplomatik yang hati-hati, tanpa penghormatan pada prinsip hukum internasional, dan tanpa pemahaman realistis tentang dinamika kekuatan kawasan, Jepang hanya akan merusak dirinya sendiri.
Tiongkok, sebaliknya, memperlihatkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu ditunjukkan dengan retorika agresif, melainkan melalui kemampuan memengaruhi arah ekonomi dan geopolitik kawasan secara efektif, cepat, dan terukur.
Oleh karena itu kebangkitan militerisme Jepang tidak boleh dibiarkan, dan eksploitasi masalah Taiwan oleh kekuatan eksternal tidak boleh menjadi pemicu perang baru di Asia Timur. Komunitas internasional harus bergerak bersama, memastikan bahwa tatanan pascaperang dijaga, perdamaian dilindungi, dan tidak ada negara yang kembali terjerumus dalam ambisi keliru yang pernah membawa dunia ke dalam kehancuran.
Karena yang dibutuhkan Asia Timur adalah stabilitas bukan konfrontasi, diplomasi bukan provokasi, dan kehati-hatian bukan retorika yang membakar. Jika Jepang gagal memahami realitas ini, maka konsekuensinya dapat menjadi bencana yang akan mengguncang seluruh tatanan global.