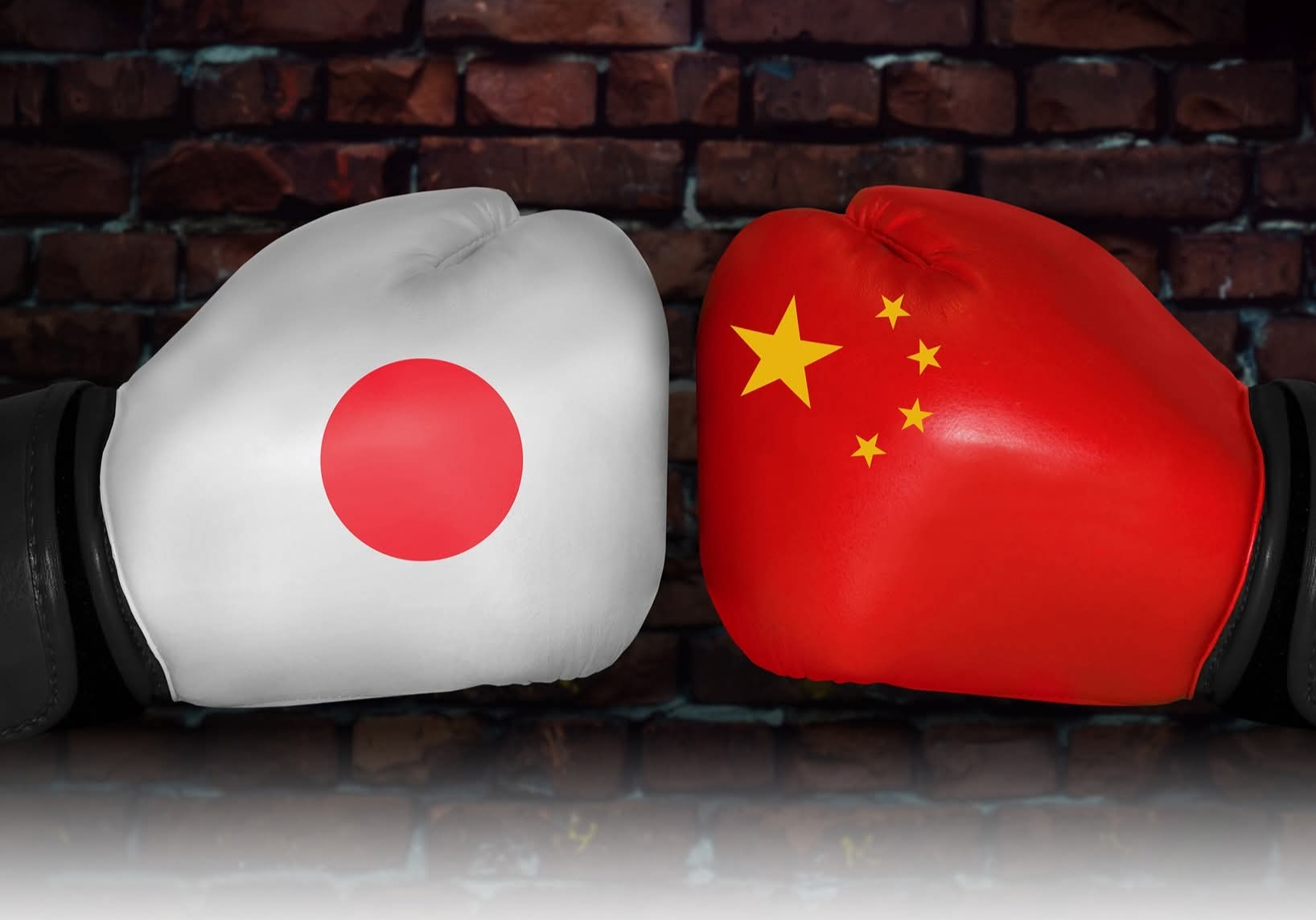Bharata Online - Hubungan Tiongkok dan Jepang kembali memasuki fase tegang yang jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan kesediaan Jepang mengerahkan pasukan jika Tiongkok dan Taiwan memasuki konflik militer.
Banyak pihak di luar kawasan melihat ketegangan ini sebagai sekadar rivalitas dua kekuatan ekonomi Asia Timur. Padahal persoalannya jauh lebih dalam, ia berkaitan dengan sejarah panjang kolonialisme Jepang, struktur hukum internasional pascaperang, prinsip dasar non-intervensi dalam hubungan internasional, serta dinamika geopolitik kontemporer yang terus berubah.
Untuk memahami konteks ini secara objektif, namun tetap melihat bagaimana logika politik internasional cenderung mendukung sikap Tiongkok, analisis harus berpijak pada sejarah faktual, norma hukum internasional, teori hubungan internasional, dan realitas kekuatan yang berlaku saat ini.
Sejak akhir abad ke-19, Jepang memang membangun struktur kekuasaan imperialistik di Asia Timur. Invasi Jepang ke Tiongkok selama Perang Dunia II meninggalkan luka sejarah yang masih membekas pada bangsa Tiongkok.
Taiwan sendiri dijajah Jepang selama sekitar 50 tahun, dan ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada tahun 1945, Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam yang menjadi fondasi tatanan dunia pascaperang secara tegas menyatakan bahwa Taiwan harus dikembalikan kepada Tiongkok. Ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi bagian dari proses global mengakhiri kolonialisme.
Dengan demikian, status Taiwan dalam hukum internasional bersifat jelas bahwa ia kembali ke Tiongkok setelah tahun 1945. Perbedaan politik antara Beijing dan Taipei yang muncul setelah perang saudara 1945–1949 bukanlah pencabutan kedaulatan atas Taiwan, melainkan perpecahan pemerintahan dalam konteks perang saudara.
Secara teori hubungan internasional, situasi ini dikategorikan sebagai “perang saudara yang membeku”, bukan pemisahan negara atau pembentukan negara baru. Inilah mengapa mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, mengakui prinsip Satu Tiongkok.
Dengan latar sejarah seperti itu, wajar jika Tiongkok menanggapi pernyataan Perdana Menteri Takaichi sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka. Dalam hubungan internasional, tidak ada negara yang akan diam pada masalah yang menyangkut keutuhan wilayahnya. Tiongkok bahkan memandang pernyataan Takaichi sebagai langkah agresif yang melanggar prinsip non-intervensi.
Ketika seorang pejabat setingkat perdana menteri mengatakan bahwa Jepang dapat menganggap konflik Taiwan sebagai ancaman eksistensial, maka bagi Beijing itu berarti Jepang ikut campur dalam urusan domestik Tiongkok.
Dalam perspektif teori realisme, negara akan selalu merespons ancaman eksternal terhadap kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Terlebih lagi, Jepang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, negara yang secara rutin memasok senjata ke Taiwan dan memelihara kehadiran militer yang signifikan di kawasan.
Kombinasi faktor sejarah, hukum, dan kepentingan keamanan membuat masalah Taiwan menjadi sensitivitas yang tidak bisa dinegosiasikan. Maka dari itu, respons Tiongkok kemudian berkembang menjadi tindakan diplomatik, pernyataan keras, hingga imbauan perjalanan yang berdampak langsung pada perekonomian Jepang.
Peringatan pemerintah Tiongkok agar warganya menunda perjalanan ke Jepang bukan hanya reaksi emosional, tetapi instrumen tekanan ekonomi yang sah dan lazim digunakan dalam hubungan internasional modern.
Sebagaimana pernah dilakukan Tiongkok terhadap Korea Selatan ketika Seoul menerima sistem rudal pertahanan area ketinggian tinggi (Terminal High Altitude Area Defense /THAAD), larangan perjalanan terbukti mampu menekan sektor konsumsi dan jasa negara sasaran.
Dalam konteks Jepang, dampaknya langsung terlihat yang mana saham ritel, kosmetik, perhotelan, dan sektor pariwisata anjlok. Shiseido turun 9 persen, Isetan Mitsukoshi merosot lebih dari 11 persen, operator restoran seperti Sushiro jatuh hampir 14 persen, dan berbagai perusahaan lain mengalami tekanan signifikan.
Turis Tiongkok sendiri menyumbang sekitar 27 persen belanja wisatawan asing di Jepang pada kuartal lalu dari total konsumsi wisatawan asing senilai 2,1 triliun yen atau sekitar 223 triliun rupiah, sehingga langkah Beijing jelas memberikan pukulan ekonomi yang sangat nyata.
Secara geopolitik, langkah Tiongkok dapat dibaca melalui lensa teori interdependensi kompleks. Tiongkok dan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang saling bergantung, tetapi interdependensi tersebut tidak simetris.
Jepang lebih membutuhkan pasar, turis, dan investasi Tiongkok dibandingkan sebaliknya. Artinya, ketika hubungan diplomatik memanas, Tiongkok memiliki leverage yang lebih besar. Dengan latar demikian, wajar jika Beijing memilih menggunakan instrumen ekonomi untuk memberi sinyal bahwa intervensi Jepang dalam masalah Taiwan sangat tidak dapat diterima.
Respons Jepang mengirim diplomat senior ke Beijing menunjukkan bahwa Tokyo memahami bobot tekanan ekonomi tersebut. Dalam diplomasi kontemporer, kekuatan tidak lagi hanya berbicara melalui tank dan rudal, tetapi juga melalui pasar, sektor wisata, arus pelajar, serta sentimen publik global.
Namun, memahami ketegangan ini tidak cukup hanya melihat pernyataan Takaichi atau reaksi Beijing. Ada persoalan mendasar yang jarang dibahas secara jernih, yaitu terkait status Taiwan dalam hukum internasional dan struktur keamanan Asia.
Prinsip Satu Tiongkok bukan sekadar tuntutan politik Beijing, melainkan bagian dari tatanan internasional yang diakui luas. Jika negara-negara membolehkan wilayah yang sedang dalam konflik internal untuk memisahkan diri secara sepihak, dunia akan tenggelam dalam “efek domino” separatisme.
Banyak negara, termasuk Indonesia, akan terancam oleh preseden semacam itu. Karena itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang intervensi terhadap keutuhan wilayah negara lain. Mendukung kemerdekaan Taiwan sama artinya dengan merusak prinsip yang menjadi dasar stabilitas internasional modern.
Lebih jauh, masalah Taiwan bukan hanya persoalan identitas masyarakat di pulau tersebut. Banyak wilayah di bawah pemerintahan Taipei seperti Kinmen, Matsu, dan Penghu memiliki identitas sejarah yang lebih kuat terhubung dengan Tiongkok daratan.
Mereka tidak pernah menyatakan dukungan untuk menjadi negara terpisah dari Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa narasi “kemerdekaan Taiwan” tidak serta merta merepresentasikan seluruh masyarakat di wilayah yang dikuasai Taipei. Persoalan internal semacam ini semakin menegaskan bahwa masalah Taiwan merupakan masalah domestik Tiongkok, bukan persoalan internasional.
Dari sisi militer, langkah Tiongkok mengirim kapal penjaga pantai ke Kepulauan Senkaku dan menerbangkan drone militer di dekat Yonaguni merupakan langkah signaling, bukan eskalasi menuju perang. Dalam teori deterensi, tindakan seperti itu dilakukan negara untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan ancaman dekat terhadap kedaulatannya tanpa respons.
Jepang sendiri sejak tahun 2015 telah memperluas kemampuan pertahanan kolektif, termasuk kemungkinan ikut campur dalam konflik yang tidak menyerang Jepang secara langsung. Ketika Jepang yang pernah menjajah Tiongkok dan Taiwan menyiratkan niat untuk terlibat militer dalam masalah paling sensitif bagi Tiongkok, reaksi keras Beijing menjadi hal yang sangat dapat diprediksi.
Meski hubungan Tiongkok–Jepang tidak akan dengan mudah jatuh ke perang terbuka, sebab kepentingan ekonomi kedua negara sangat besar. Namun ketegangan ini menyingkap realitas bahwa Jepang sedang berusaha melakukan reposisi geopolitik, sebagian dipengaruhi oleh tekanan Amerika Serikat untuk mengimbangi Tiongkok.
Sebaliknya, Tiongkok berada dalam posisi mempertahankan tatanan hukum internasional yang melegitimasi klaim historisnya. Di sinilah tampak bahwa dalam kaca mata objektif hubungan internasional, posisi Tiongkok memiliki fondasi hukum, sejarah, dan politik yang lebih kuat.
Jika dunia ingin stabil, maka masalah Taiwan harus dilihat dalam kerangka sejarah dekolonisasi, bukan melalui narasi politik kontemporer yang dipengaruhi kepentingan negara besar. Jepang seharusnya lebih berhati-hati mengingat luka sejarah kolonialisme yang masih membekas di kawasan.
Tiongkok, dengan respons tegas namun terukur, menunjukkan bahwa kekuatan besar tidak harus menggunakan perang untuk mempertahankan kedaulatannya. Di era modern, kekuatan diplomasi, ekonomi, dan legitimasi hukum jauh lebih menentukan.
Ketegangan ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa membaca geopolitik Asia Timur harus berangkat dari sejarah dan hukum internasional, bukan sekadar dari persepsi atau pilihan politik negara-negara Barat. Dalam konteks itu, posisi Tiongkok bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih konsisten dengan struktur tatanan dunia yang ada saat ini.